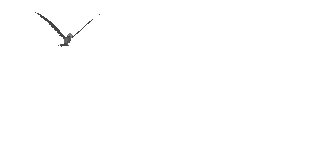dengan 37 komentar
Merekalah bocah-bocah yang selalu bahagia. Jika malam tiba, mereka akan berlari-lari girang, mengejar-ngejar dan menggapai-gapai kunang-kunang yang berkerlap-kerlip melayang-layang serupa sebaran serbuk cahaya. Mereka jugalah bocah-bocah yang menghadirkan tawa dan canda di lembah itu hingga membuatnya hidup, terasa dihuni.Selebihnya adalah gelap. Listrik belum masuk dan orang-orang dewasa terlalu sibuk dengan urusan ranjang. Maka, belum genap malam, bocah-bocah pun diusir pergi ke luar rumah, ke surau untuk mengaji atau berlatih silat ke lapangan sepak bola asalkan jangan bermain kunang-kunang. Karena bagaimanapun, orang-orang tua tetap meyakini kunang-kunang sebagai jelmaan kuku-kukunya orang mati. Jika menjadikannya sebagai mainan, maka akan menyebabkan kesialan.
Untunglah sekumpulan bocah-bocah pencinta kunang-kunang ini mendapatkan pelajaran ilmu kehewanan di sekolah sehingga mereka tahu bahwa kunang-kunang tak lebih dari sejenis serangga yang bisa mengeluarkan cahaya yang akan tampak jelas jika gelap malam menyungkup dunia. Mengapa kunang-kunang bisa menghasilkan cahaya dan mengapa dengan cahaya itu tubuhnya sendiri tidak kepanasan atau terbakar, tentu juga bukan lagi menjadi rahasia bagi mereka.
Pak Guru Sadirun pernah menguak semua rahasia mengenai makhluk yang bernama kunang-kunang itu. Berdasarkan buku teks pelajaran, Pak Sadirun menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya, kunang-kunang memiliki zat kimia lusiferin dan enzim lusiferase. Untuk menghasilkan cahaya, dua zat ini bercampur. Percampuran ini menghasilkan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya itu pun sifatnya dingin, tidak mengandung ultraviolet dan sinar inframerah. Ia memiliki panjang gelombang 510 hingga 670 nanometer dengan warna merah pucat, kuning, atau hijau. Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan familia dalam ordo kumbang Coleoptera. Ada lebih dari dua ribu spesies kunang-kunang yang dapat ditemukan di daerah empat musim dan tropis di seluruh dunia. Spesies ini dapat ditemukan di rawa atau hutan yang basah di mana tersedia banyak persediaan makanan untuk larvanya.
Maka, dengan berkah pengetahuan itu, bocah-bocah ini menjadi tak pernah khawatir dengan larangan orangtua mereka dan mereka tak pernah takut akan kesialan. Bagaimanapun, mereka tetap berlomba-lomba menangkap kunang-kunang. Siapa yang mendapat paling banyak akan dinobatkan sebagai Raja Kunang-kunang. Kesenangan dan kebahagiaan itu tak tergantikan. Hingga, akhir-akhir ini mereka pun tak lagi mendatangi guru mengaji atau guru silat mereka karena kunang-kunang memiliki lebih banyak pesona.
Untuk menghadirkan kunang-kunang, mereka biasanya mendendangkan berulang-ulang nyanyian kunang-kunang itu:
Hai kunang-kunang, datanglah, datanglah…..
Jangan malu-malu pada rindu malam-malam…..
Hai kunang-kunang datanglah, datanglah…..
Jangan ragu-ragu kami tunggu, kami rindu…..
Kunang-kunang sepertinya sudah begitu akrab dengan suara-suara itu sebab setelah nyanyian itu mengalir, sekumpulan kunang-kunang dari semak, dari pepohonan, dan dari mana pun akan melayang-layang menyatu menyerbu para bocah itu, merelakan diri untuk ditangkap tangan-tangan lugu, tangan-tangan milik makhluk yang tak punya hasrat membunuh, mereka yang hanya ingin bermain dan menikmati permainan masa kanak yang bukanlah lagi menjadi suatu bagian diri jika kelak mereka dewasa. Bagaimanapun, tangan waktu dan zaman akan berperan mengubah mereka.
Kunang-kunang yang tertangkap akan dikumpulkan di dalam botol masing-masing. Jika malam sudah genap dan embusan angin lembah mulai membuat kunang-kunang melayang tak tentu arah, maka mereka akan berhenti dan mulai menghitung hasil tangkapan mereka di pos ronda.
Tak ada yang bisa menyaingi rekor predikat Raja Kunang-kunang yang sudah dibuat oleh Yasser Arafat. Hampir selalu, bocah bertinggi badan melebihi sebayanya ini menjadi pengumpul terbanyak. Bagaimana tidak, dia memiliki jangkauan lompatan tertinggi. Dia juga yang paling kuat berlari. Pernah memang, predikat Raja Kunang-kunang menjadi milik Anhar Alifudin. Itu terjadi semata karena Yasser Arafat yang sakit tidak bisa ikut bermain.
Malam ini, Yasser Arafat berhasil mengumpulkan lima puluh kunang-kunang. Kontras dengan Baraq Syariati yang hanya mendapatkan lima kunang-kunang. Dengan badannya yang kecil, Baraq tak pernah mampu melompat lebih tinggi. Juga tak kuat berlari. Dengan begitu, dialah yang selalu menjadi pecundang sejati dan rutin menjalani hukuman dengan mencabut dan mengambil singkong dari kebun milik orang terkaya di dusun itu: Juragan Hussein Akbar.
Usai dihitung semua dan Raja Kunang-kunang sudah diketahui siapa, maka kunang-kunang kembali dilepas. Bocah-bocah bersorak dan kunang-kunang berkerlap-kerlip riang, merasa bangga sudah bisa menghibur sekaligus terhibur berkat tingkah bocah-bocah lugu itu.
Dingin mulai menusuk. Bocah-bocah mengembangkan sarung dan memakaikannya ke badan. Ranting-ranting kering dikumpulkan dan dibuatlah api unggun pengusir dingin di depan pos ronda. Setibanya Baraq Syariati yang membawa singkong-singkong dari kebun Juragan Hussein Akbar, mulailah mereka memanggang.
Kenyataannya, pos ronda yang sudah menjadi markas mereka itu tak pernah lagi digunakan. Orang-orang tua di lembah itu tak bisa setia menjalankan apa yang sebenarnya sudah mereka rancang sendiri. Jika mengharapkan partisipasi para pemuda, tentu tidak bisa sebab semua pemuda dari dusun itu merantau ke kota-kota. Giliran ronda untuk bapak-bapak memang pernah berjalan. Namun, karena dingin lembah itu tak tertahankan dan wajah istri selalu membayang, serta tak pernah ada peristiwa kemalingan, mereka pun tak lagi setia dengan kewajiban masing-masing. Fakta itu justru membuat bocah-bocah pencinta kunang-kunang ini senang. Mereka mendapatkan markas untuk rehat usai bermain.
Sehabis menyantap singkong panggang, tentu banyak angin yang harus dibuang. Dan, bocah-bocah itu menjadikannya sebagai bahan permainan selanjutnya, yaitu perang kentut. Kemenangan dan predikat sebagai Raja Kentut sama prestisiusnya dengan Raja Kunang-kunang. Bagaimanapun, penilaian tidak didasarkan semata pada bunyi yang dihasilkan, tapi juga pada bau yang mematikan. Jika kentutnya berbunyi keras dan berbau busuk, tak diragukan lagi dialah sang juara sejati. Untuk urusan yang satu ini, pemegang rekornya adalah Hang Jebad, bocah paling tua di kumpulan itu.
Biasanya, sehabis perang kentut, malam sudah larut sempurna. Bocah-bocah menyadari itu dan pulanglah mereka segera dan tidur lelap setibanya mereka di pembaringan.
Bocah-bocah pencinta kunang-kunang berkumpul seperti biasanya malam ini. Di sekitar tanah lapang, tak jauh dari semak. Mereka melantunkan dendang kunang-kunang, mengundang kunang-kunang untuk datang bermain bersama sebagaimana biasa:
Hai kunang-kunang, datanglah, datanglah…..
Jangan malu-malu pada rindu malam-malam…..
Hai kunang-kunang datanglah, datanglah…..
Jangan ragu-ragu kami tunggu, kami rindu…..
Meski telah diulang-ulang berpuluh-puluh kali, dendang itu tak sanggup mendatangkan kunang-kunang. Mereka menjadi heran. Setahu mereka, semenjak pertama mendendangkan nyanyian sekaligus mantra pemikat itu, ratusan kunang-kunang terindah dari segenap penjuru lembah selalu berdatangan. Namun, malam ini, semuanya terasa lain, tak ada kunang-kunang yang berkerlap-kerlip terbang mendekat. Maka, lembah itu pun benar-benar menjadi mati dan bocah-bocah itu, untuk kali pertama dirasuki kekecewaan. Apa yang terjadi? Apakah ada kumpulan bocah-bocah lain yang membuat kunang-kunang itu lebih tertarik mendekat ke sana? Bocah-bocah itu tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab.
Malam makin pekat dan awan menghitam dan hujan pun tumpah. Bocah-bocah berlari-lari dalam hujan, berupaya menggapai pos ronda. Di pos ronda, dalam hawa yang dinginnya melumat tulang, bocah-bocah itu membuat diri senyaman-nyamannya dalam penantian. Hujan tampaknya tak segera habis dalam waktu dekat. Anak-anak memutuskan untuk tetap bertahan. Percuma juga mereka pulang di malam yang belum genap seperti sekarang karena pintu rumah masih rapat terkunci. Barulah dibuka kuncinya jika malam sudah larut dan orang tua mereka sudah menyelesaikan ritual hiburan ranjang.
Dalam hujan badai dengan angin yang merontokkan dedaunan itu, bocah-bocah itu mendengar derum sebuah truk yang tenggelam dalam tunggal nada hujan. Jauh dari sini, mereka bisa menangkap—meski tak begitu jelas—gerakan lamban truk itu di sana. Awalnya mereka mengira itu truk milik Juragan Hussein Akbar yang biasa pulang malam sehabis menjual hasil pertanian ke kota, tapi nyatanya bukan. Truk milik Juragan Hussein Akbar berwarna kuning. Meski dalam gelap, kuningnya tetap akan terlihat dari kejauhan. Tetapi, truk yang satu itu berwarna gelap dan tertutup tenda di bagian belakangnya. Tak berapa lama kemudian, truk itu berhenti di tepi jurang.
”Mungkin mesinnya mogok.”
”Mungkin bannya terendam lumpur.”
Mereka pun hanya bisa mengira-ngira apa yang melanda truk itu karena gelap kembali berkuasa setelah dua lampu sorot pada truk itu mati. Truk itu berhenti sekitar setengah jam lamanya di sana dan bocah-bocah pencinta kunang-kunang masih juga berteduh menanti hujan berhenti.
Kedua lampu pada truk itu hidup lagi dan truk itu bergerak perlahan meninggalkan tepi jurang kemudian berbelok di pertigaan, mengambil jalan ke arah kecamatan. Bocah-bocah itu hanya melihat kepergian truk itu dari kejauhan.
Beberapa jam sepeninggalan truk itu, hujan pun reda. Malam sudah larut dan bocah-bocah itu memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, mereka segera membatalkan niat itu setelah melihat kemunculan kerlap-kerlip kunang-kunang di sekitar tepi jurang, di lokasi berhentinya truk tadi.
Maka, bocah-bocah itu pun berlari riang ke arah kunang-kunang itu dengan segera. Semakin banyak kunang-kunang, semakin girang bocah-bocah. Satu hal yang pasti, kunang-kunang itu tampak tak banyak beranjak. Mereka hanya mengambang bertahan di atas jurang. Meski bocah-bocah sudah mendekat, tetap saja kunang-kunang tak terbang.
Setiba mereka di tepi jurang, bocah-bocah itu didekap rasa penasaran menyaksikan kunang-kunang yang semakin banyak bermunculan dari dasar jurang yang gelap. Bocah-bocah itu tak jadi menangkap kunang-kunang itu. Mereka justru turun ke dasar jurang demi memastikan apa yang ada di sana.
”Mungkin di sana ada kerajaan kunang-kunang.”
”Mungkin….”
Pelan-pelan, mereka menapaki jalan kecil menuju jurang yang licin dan basah. Sesampai mereka di dasar jurang, Baraq Syariati terjatuh. Ia tersandung sesuatu. Anhar Alifudin segera menyalakan senter. Gelap sedikit terusir dan mereka kini mengetahui bahwa Baraq terjatuh karena tersandung sesosok tubuh, sesosok mayat.
Serta-merta mereka dilanda kepanikan yang tak tanggung-tanggung karena tak hanya ada satu mayat saja. Di situ menumpuk banyak mayat dan sudah berbau busuk dan kunang-kunang indah pun semakin banyak. Mulanya kuku-kuku yang terlepas dari jari kaki dan tangan mayat-mayat itu mengambang untuk kemudian menjelma titik-titik cahaya, menjadi kunang-kunang yang indah rupa.
Tak bisa tidak, bocah-bocah itu pun berlari ketakutan meninggalkan jurang itu, meninggalkan tumpukan-tumpukan orang mati dengan luka-luka tembak itu, meninggalkan ribuan kunang-kunang dengan keindahan yang memesona, makhluk-makhluk baru yang menjelma dari kuku-kuku mayat-mayat yang dilemparkan begitu saja dari dalam truk tadi.
Maka, malam itu, wajah dusun kecil di lembah tersebut menjadi terang benderang sebab beribu-ribu kunang-kunang yang baru lahir berpesta dan inilah malam terindah milik mereka semata: malam kunang-kunang.